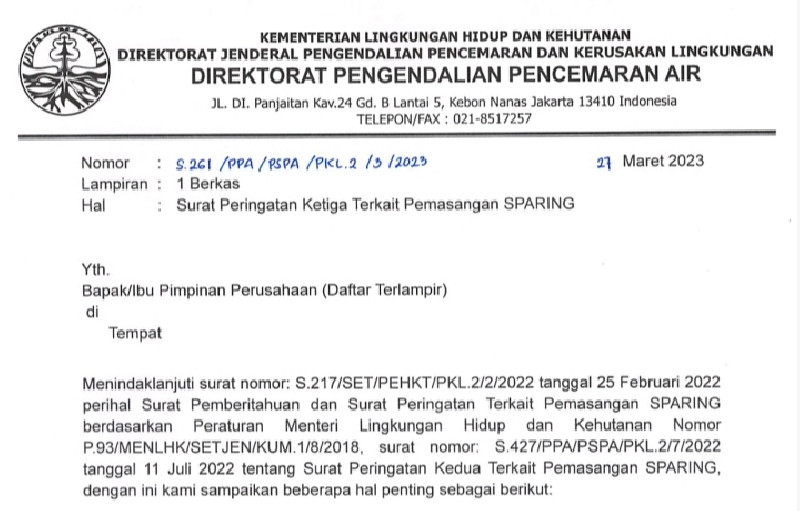Bermain Di Kopelma
Font: Ukuran: - +
.jpg)
Oleh: Otto Syamsuddin Ishak
Suatu ketika, saya tak ingat lagi waktunya, mungkin sekitar akhir 1970, WS Rendra mementaskan lakon “Oedipus Rex” di halaman dalam Fakultas Ekonomi, Universitas Syiah Kuala.
Usia saya saat itu memang belum bisa memahami lakon yang dipentaskan. Rendra berperan sebagai raja Thebes, dan istrinya berperan sebagai permaisuri, yang dalam lakon itu, ternyata juga sekaligus ibunya Oedipus.
Thebes dilanda wabah dan huru-hara, akibat kemungkaran para dewa karena pembunuh Raja Laius belum dihukum. Oedipus sendiri bertanya-tanya, siapakah gerangan pembunuh raja itu? Di lain pihak, hoax dan doxing menyerbu segala penjuru Thebes.
Krisis kesehatan dan politik di Thebes menggoncangkan jiwa Oedipus. Pasalnya dia menjadi ingat pada ramalan Dewa Apollo, bahwa suatu ketika nanti Oedipus akan membunuh ayahnya sendiri, Raja Laius, lalu ia akan mengawini ibunya sendiri, Ratu Yocasta.
Di akhir babak sandiwara itu, Oedipus mengambil tusuk konde di sanggul sang istri, yang sekaligus ibunya itu, lalu ia menusuk matanya sendiri hingga berdarah dan membuta. Ratu Yocasta pun membunuh diri.
50-an tahun sudah berlalu sejak pementasan teater yang dipimpin Rendra dan sekaligus menciptakan mars Darussalam. Saya duduk di warung kopi simpang Tanjung Selamat. Saya bertanya pada diri sendiri.
Mengapa terjadi huru-hara terkait dengan kebijakan penggusuran di Kopelma Darussalam? Apakah alur dinamika kehidupan di Kopelma Darussalam mengikuti pola ramalan Dewa Apollo itu?
Dalam perspektif sosiologis Weberian; mungkinkah, kehidupan di Kopelma Darussalam telah menjelma menjadi kehidupan yang berada di dalam “sangkar besi” sebagaimana yang diproyeksikan oleh Weber?
Di mana pengorganisasian kampus semakin terbirokratisasi, yang digerakkan oleh generasi yang memiliki jarak waktu 60 tahun dengan awal proses mendirikan Kopelma Darussalam. Ribuan rakyat Aceh dikerahkan untuk ber-gotongroyong.
Sekarang perguruan tinggi yang ada di Kopelma Darussalam telah menjelma menjadi sebuah sangkar besi yang diatur dengan formalisme birokrasi, yang mana birokrasi itu sendiri menurut Weber, adalah perwujudan dari rasionalitas yang kian meninggi, yang sebaliknya, justru memiliki kadar kemanusiaan yang kian menurun.
Pada 30 Januari 1961, sebagai Gubernur Aceh, Ali Hasjmy mengeluarkan sebuah pengumuman No. Agr. 3/1961, berdasarkan Undang-undang No. 5 tahun 1960, pertama, “kepada para pemilik/pemegang hak erfpacht atas tanah erfpacht jang letaknja dalam Daerah Istimewa Atjeh dilarang mendjual, menjerahkan atau menjewakan….tanpa izin lebih dahulu dari kami.” Kedua, “…dilarang menjerahkan haknja itu kepada siapapun djuga tanpa izin lebih dulu dari kami.”
Kopelma Darussalam berkembang pesat dalam masa 20-an tahun. Birokrasi perguruan tinggi pun semakin rasional sejalan dengan pergantian generasi yang lebih rasional pula. Ali Hasjmy sendiri sudah beralih dari seorang Gubernur menjadi seorang pimpinan perguruan tinggi.
Ali Hasjmy yang mulai gelisah di masa akhir jabatannya sebagai Rektor IAIN Jami’ah Ar-Raniry menuangkan kegelisahannya dalam sepucuk surat yang tertanggal 11 Oktober 1982. Surat itu dilayangkan kepada Gubernur Dista Aceh.
Intinya, beliau mengatakan bahwa lahan Kopelma Darussalam yang luasnya sekitar 200 Ha adalah disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Universitas Syiah Kuala dan IAIN Jami’ah Ar-Raniry. Namun, tragisnya, secara sepihak lahan itu kemudian dialihkan ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Sehingga IAIN “seakan-akan tidak mempunyai hak sejarah apapun. Sungguh amat tragis… Keadaan ini adalah sangat rawan dan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan…”
Sebelum menutup suratnya, Ali Hasjmy mempertanyakan: “Bagaimana perasaan kemanusiaan Rakyat Aceh kalau diketahuinya bahwa hak IAIN Jami’ah Ar-Raniry dari tanah tersebut telah dialihkan kepada lembaga lain?”
Namun, kekacauan itu telah terlebih dahulu ditangkal oleh ahli waris T. Nyak Arief. Bahwa atas nama ahli waris hak erfpacht “Roempit”, T. Syamsulbahri menulis sepucuk surat tertanggal 3 September 1975, yang intinya adalah pelepasan hak.
Hal ini menyusul dikeluarkannya Akte Notaris Abdul Latief yang dibuat pada 10 Juni 1975, yang diketahui oleh Pimpinan Proyek M. Hasbuh Azis. Begitulah, surat itu telah membebaskan keluarga ahli waris dari ramalan dewa Apollo atau praktek sangkar besi generasi pengelola kampus saat ini. Sungguh sangat mulia.
Tiba-tiba, seseorang menegur saya hingga terjaga dari lamunan. Ia adalah warga kampung Tanjung Selamat. Dia bertanya; apakah kamu masih ingat dengan saya? Saya terdiam, seraya mencoba membongkar memori puluhan tahun lalu.
Dia terus memantik ingatan saya; kita pernah main layangan, gasing di sekitar Tugu Darusalam, yang merupakan symbol jantung hati rakyat Aceh. Kita pernah main bolakaki bersama.
Namun, setelah itu paha saya dan beberapa paha kawan lain,membengkak di malam hari. Kata para orangtua, hal itu akibat kita bermain bola di atas kuburan para syuhada dan aulia.
Sungguh, dalam jangka waktu sekitar 60-an tahun telah terjadi berbagai bentuk transformasi di lahan erfpach yang dahulu kaya dengan sakralitas, kini telah menjadi lahan berdirinya sangkar besi yang kadar rasionalitasnya kian meningkat, dan sebaliknya kian kehilangan kadar kemanusiaannya.
Andaikan kisah Raja Thebes, Oedipus muncul di Darussalam, apakah ia juga akan meminta dirinya untuk dibuang dari istana, setelah ia membutakan dirinya sendiri? Namun, drama Oedipus itu bukanlah dikonstruksi dari konteks keacehan.
Kembali kepada cerita warga Tanjung Selamat di atas, maka paling tidak, kakinya akan membengkak di setiap malam bilamana ia terus bermain bola di atas lahan yang banyak bertebaran kuburan dan bangunan dari wakaf para leluhur, dengan tanpa kesantunan.*
*Penulis adalah sosiolog, tinggal di Banda Aceh.
Berita Populer







 Sebelumnya
Sebelumnya